Kalah dalam permainan kelompok bagi sebagian anak-anak menimbulkan emosi negatif: kecewa, malu, bahkan bisa kehilangan kepercayaan diri. Saya ingat suatu hari ketika anak sulung saya masih duduk di bangku Taman Kanak-kanak. Saat itu sekolahnya mengadakan acara bermain bersama orangtua murid. Para orangtua berkumpul di tengah lapangan dengan satu balon kecil yang diikatkan ke pergelangan kaki. Orang lain harus menginjak balon itu untuk dipecahkan. Pada akhir waktu yang ditentukan, orang dengan balon yang masih utuh adalah yang menang. Anak saya menarik-narik lengan saya agar saya tidak masuk ke tengah lapangan. Dia memohon, “Mami, jangan ikut main, nanti mami kalah.” Kekhawatiran akan kekalahan membuat dia memilih langkah yang paling aman — tidak ikut bermain.
Kita hidup dalam kebudayaan “selalu tidak cukup”. Tidak cukup baik, tidak cukup pintar, tidak cukup langsing, tidak cukup berusaha. Orangtua selalu meminta anak-anak untuk “do your best”– kerjakan dengan segenap kemampuanmu. Tapi bagaimana kita tahu mereka telah mengerahkan seluruh kemampuannya? Ketika hasil pekerjaan tidak memuaskan, mungkin mereka takut dicap tidak “did their best”, tidak cukup berusaha, tidak cukup cerdas. Dalam segala ketidak-cukupan ini, kita tumbuh dan ketakutan. Ketika anak kita akan ikut acara sekolah berkemah tiga hari untuk pertama kalinya, kita ketakutan, apakah cukup aman?
Teman akrab saya pernah bercerita ketika anaknya masih berumur beberapa bulan. Dia sering terbangun tengah malam untuk mengintip anaknya, tidak jarang dia mendekatkan jarinya ke hidung anaknya untuk membuktikan bahwa anaknya masih bernafas. Takut akan hal buruk yang mungkin terjadi membuat dia tidak bisa sepenuhnya menikmati kebahagiaan.
Dr. Brené Brown dari Universitas Houston- pengarang buku Daring Greatly: How the Courage to Be Vulnerable Transforms the Way We Live, Love, Parent, and Lead, mengatakan, masyarakat kita sekarang kehilangan toleransi terhadap kerentanan/ketidakkebalan (vulnerability). Dari kecil kita mengajari diri sendiri dan selanjutnya mengajari anak-anak kita untuk mengalahkan kerentanan itu. Kita berusaha mengubah semua situasi menjadi sesuatu yang pasti. Jika kamu tidak pasti bisa menang, jangan ikut lomba. Jika kamu tidak yakin kue itu enak, jangan dimakan, nanti tidak bisa kamu habiskan. Ini membuat kita tidak mampu secara penuh menikmati apa yang tidak pasti. Iman, cinta, kepercayaan, kebahagiaan, kreativitas, semua adalah hal yang tidak pasti.
“Vulnerable” menurut kamus Merriam-Webster berarti: mudah terluka secara fisik, mental, ataupun emosional. Terpapar pada serangan, bahaya, atau kerusakan. “Rentan” dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti: mudah terkena penyakit, peka, mudah merasa. Kata “vulnerable” memberikan rasa kata “lemah”, walau kata rentan lebih memberikan rasa seperti itu karena dalam artinya tidak tercantum “terpapar” seperti pada “vulnerable”.
Di tengah kehidupan penuh hal negatif seperti bully, kekerasan, kesedihan, bahaya dan ancaman, tidak mengherankan jika orangtua cenderung overprotektif terhadap anak-anaknya. Orang dewasa melakukan hal yang sama terhadap diri sendiri. Dalam tumbuh kembang kita, secara sadar maupun tidak, kita berusaha untuk menghindar dari sesuatu yang mungkin bisa melukai. Kita membuat diri kita mati rasa. Hal ini bisa terlihat pada banyaknya orang yang kecanduan –kecanduan rokok, obat-obatan, kesibukan, hal-hal yang membuat kita lupa bahwa kita rentan.
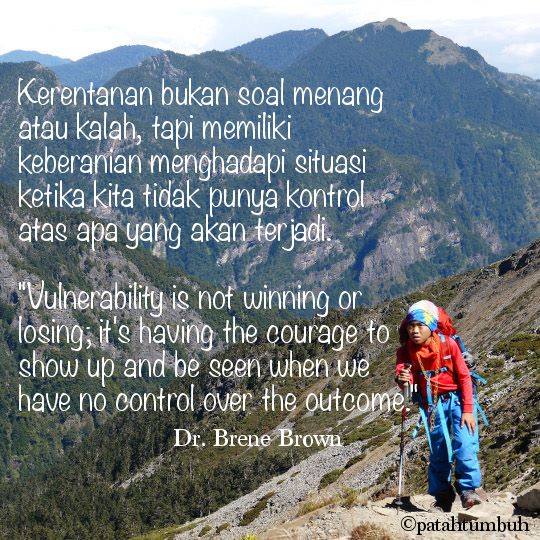
Mungkin tidak ada orang yang ingin dikatakan “lemah”. Menurut Dr. Brené Brown, kerentanan bukan kelemahan. Ia berada tepat di tengah ketakutan, keresahan, aib, dan berbagai emosi sulit yang kita alami. Tapi ia juga adalah sumber kegembiraan, cinta, belonging (perasaan memiliki/menjadi bagian), kreativitas, dan faith (iman).
Konsekuensi dari membuat diri mati rasa –menekan segala emosi termasuk kerentanan itu adalah kita juga mati rasa terhadap emosi positif. Kita bisa jadi mati rasa terhadap kegembiraan, cinta, rasa memiliki, rasa percaya, karena untuk jatuh cinta, terhadap orang ataupun pekerjaan berarti terpapar/rentan terhadap konsekuensi yang hadir bersama semua perasaan itu –dikhianati, kekecewaan, dan lain-lain.
Menurunnya kemampuan untuk mentolerir kerentanan juga dapat kita lihat pada ekstrimis. Faith is the vulnerability that flows between the shores of certainty (Iman adalah kerentanan yang mengalir di antara pantai kepastian), kata Dr. Brené Brown. Kepercayaan pada dasarnya adalah hal yang rentan, percaya pada hal yang tidak sepenuhnya dimengerti dan tidak kelihatan. Iman tanpa kerentanan membuat orang menjadi fanatik- ekstrimis.
Jadi, bagaimana kita menerima dan berdamai dengan kerentanan?
1. Bersyukur
Imbangi hal negatif dari media dan sekitar dengan syukur atas apa yang kita miliki –keluarga, teman, alam, dan semua yang ada, yang kita abaikan karena terlalu sibuk merasa tidak cukup.
2. Hargai sesuatu yang “biasa-biasa” saja.
Kita sering merasa atau membuat anak-anak/orang lain berpikir bahwa hidup yang biasa-biasa adalah hidup tanpa arti. Dalam mengejar keunikan, kita lupa bahwa momen penuh gelak tawa dan bahagia yang kita alami sehari-hari bukan hanya momen yang luar biasa.
3. Terimalah bahwa tidak ada sesuatu yang pasti, yang dapat diramalkan hasilnya. Jangan biarkan rasa takut akan hal yang tidak pasti merampas kesempatan mencicipi kegembiraan dan kebahagiaan.




















Leave a Reply