Sebelumnya: Miskin Itu Relatif (Bagian 1)
Suatu sore beberapa bulan setelah saya menikah, Bu Sri main ke rumah saya bersama anaknya, Riris. Seperti biasa Riris hampir tak pernah turun dari gendongannya. Kalau diturunkan, Riris akan duduk diam saja. Saya sering heran melihat anak itu. Jarang sakit tapi tidak kelihatan sehat dan tidak aktif seperti anak lain. Saya ingin sekali menggendong dan memeriksa dia, tapi dia tidak mau dipegang orang lain selain ibunya.
Saya: Riris ini sebenarnya sudah umur berapa?
Bu Sri: Hampir empat tahun, Bu. (Badan Riris saya lihat hanya sebesar anak umur dua tahun yang sangat kurus)
Saya: Dia tidak kuat makan ya?
Bu Sri: Kuat, Bu. Tapi dia gak bisa besar.
Saya (dalam hati saja) - Ah, kayaknya anak ini kurang gizi.
Bu Sri: Dia pernah kepijak sama bapaknya waktu masih bayi, Bu.
Saya: Hah? Kok bisa?
Bu Sri: Bapaknya mau usir kucing yang nyuri ikan asin kami, dia kejar dan gak lihat Riris di lantai, jadi kepijak dadanya.
Saya: Ampun…. Terus gimana?
Bu Sri: Ya Riris nangis.
Saya: Tak dibawa ke dokter?
Bu Sri: Waktu itu belum ada dokter, Bu.
Saya (dalam hati) - duh, gobloknya aku … Membayangkan dada bayi Riris kepijak bapaknya yang sudah rada tua itu (Ibu Riris adalah istri kedua) membuat hati saya hancur, seolah-olah hati saya yang kepijak.
Bu Sri kemudian bercerita tentang temperamen suaminya, dia sering dimarahi, bahkan dipukul. Dia bilang ingin minta cerai tapi takut dengan nasib kedua anaknya. Setiap hari Bu Sri menggendong Riris bekerja di sawah. Anaknya yang pertama- laki-laki, baru berusia tujuh tahun dan duduk di kelas satu Sekolah Dasar, dan setiap pulang sekolah akan menanak nasi. Bu Sri pulang dari sawah membawa daun singkong atau sayur apa saja yang dia tanam untuk direbus. Itulah makanan mereka sehari-hari.
Setelah hari itu, Bu Sri semakin sering ke rumah saya. Kami selalu berkomunikasi dengan bahasa lokal. Suatu hari saya menawarkan untuk membawa Riris ke Medan untuk diperiksa kesehatannya secara lengkap.
Bu Sri: Dia mana mau pisah dari saya, Bu.
Saya: Kalau begitu kamu ikut juga. Kalau perlu saya minta cuti seminggu, kita tinggal di Medan selama seminggu untuk periksa kesehatan Riris secara menyeluruh. Saya ingin tahu mengapa dia kecil begini. Jangan kuatir, semua biaya saya yang tanggung, kamu tinggal ikut saja. Gak perlu bawa sepeser pun.
Bu Sri: Saya pikir dulu ya, Bu.
Setelah itu beberapa kali saya menanyakan keputusannya tanpa mendapat jawaban pasti. Saya sudah beberapa kali pulang ke Medan pada akhir minggu tanpa berhasil membawa Bu Sri dan Riris. Akhirnya setelah beberapa bulan, saya diberi jawaban bahwa dia tidak bisa ikut saya ke Medan. Tidak ada alasan. Saya patah hati. Saya berpikir lama, tidakkah tawaran saya cukup menggiurkan? Apa yang membuat Bu Sri menolak? Bukankah dia orang “miskin” yang memerlukan bantuan? Bukankah kalau dia menerima tawaran saya, ada kemungkinan Riris menjadi anak yang tumbuh sehat? Tampaknya saya harus mengubah prasangka saya bahwa setiap orang “miskin” akan melompat menyambar setiap tawaran bantuan.

Selanjutnya: Dokter Jatuh Sakit (Bagian 1)




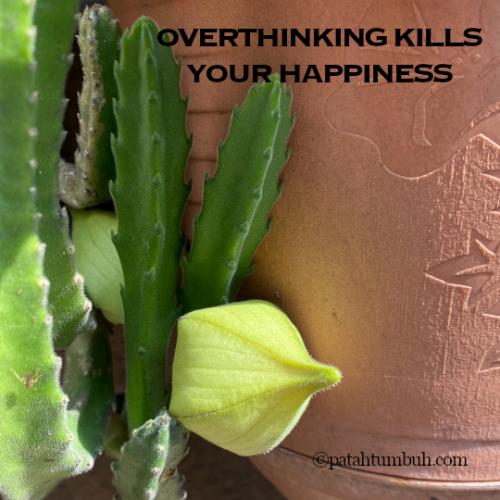

Add new comment